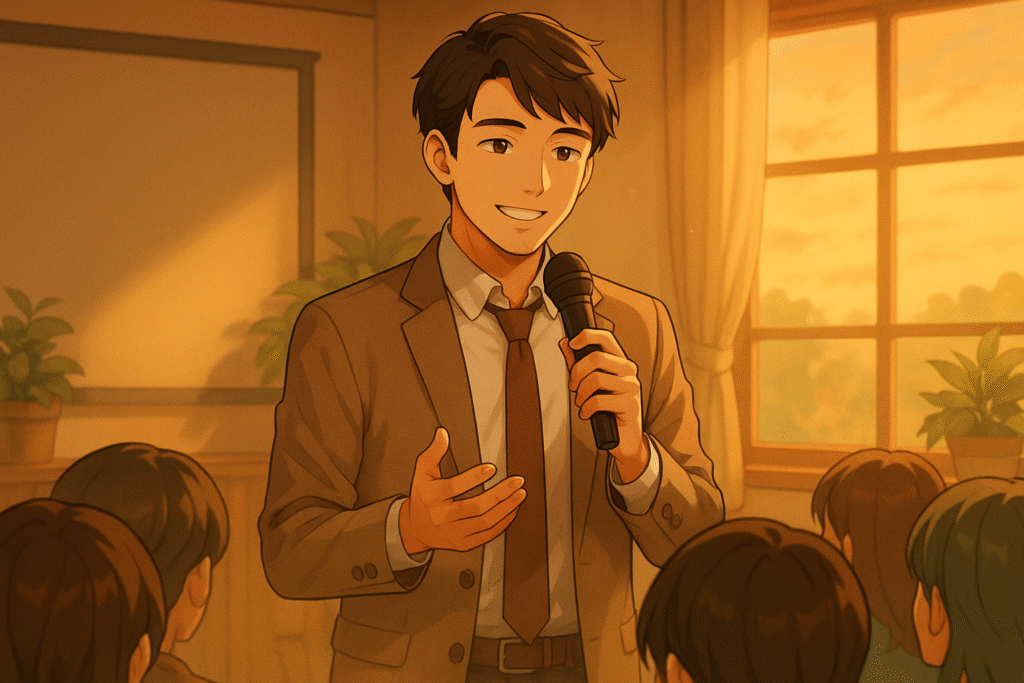Menjadi hipnoterapis dan trainer membuatku bertemu begitu banyak wajah manusia. Sebagian datang dengan semangat, sebagian lain datang dengan mata yang menyimpan lelah. Ada yang hidupnya terasa berhenti setelah kehilangan, ada yang bertahun-tahun berjuang dengan rasa tidak cukup, dan ada pula yang sekadar ingin mengerti kenapa hatinya terasa kosong meski semua terlihat baik-baik saja.
Di ruang-ruang itu aku belajar satu hal penting: manusia tidak pernah benar-benar lemah. Kadang mereka hanya lupa bahwa mereka pernah kuat. Inilah mengapa resilience (daya lenting diri) menjadi hal yang sangat dekat di hatiku. Ia bukan sekadar teori psikologi positif, tapi napas yang nyata dalam setiap proses pemulihan dan pemberdayaan diri.
Resilience: Bukan Sifat, Tapi Proses
Luthar (2014) menulis, “Resilience is not a trait, but a process.”
Ketahanan bukanlah sifat bawaan, melainkan perjalanan yang terbentuk melalui pengalaman dan hubungan.
Aku melihatnya setiap kali seseorang mulai sadar bahwa ia tidak sendiri.
Ketika klien di depanku yang tadinya menangis karena kehilangan mulai tersenyum kecil dan berkata, “Saya ternyata bisa, ya?”
Itulah momen ketika resilience bekerja.
baca juga : Hidup Bukan Tentang Kontrol, Tapi Tentang Melepaskan
Sebagai hipnoterapis, aku tahu setiap luka menyimpan memori dan emosi yang menunggu untuk dikenali. Saat seseorang belajar menenangkan tubuhnya, mengatur napasnya, dan memberi ruang bagi emosinya, ia sedang membangun jalur baru dalam otaknya (neural pathway) yang membuatnya lebih siap menghadapi hidup.
Fredrickson (1998) menyebutnya broaden and build process: emosi positif tidak hanya membuat kita merasa lebih baik, tapi juga memperluas cara kita berpikir dan memperkuat ketahanan diri.
Resilience Tumbuh Dalam Hubungan
Namun, resilience tidak tumbuh dalam kesunyian. Ia butuh hubungan dengan diri sendiri, orang lain, dan sesuatu yang lebih besar dari diri. Seligman (2002) menyebutnya flourishing atau keadaan ketika kita tidak hanya hidup, tetapi berkembang melalui makna, hubungan, dan kontribusi. Di ruang pelatihan, aku sering melihatnya muncul dengan sederhana yaitu dari tawa bersama, pelukan setelah refleksi, hingga diam yang hangat ketika seseorang berkata, “Aku siap memaafkan.”
Belajar dari Pelatihan di Poso

Menjadi trainer memberiku kesempatan untuk melihat resilience dalam skala lebih luas.
Di Pelatihan “Menjadi Orang Tua di Tengah Badai” (Yayasan Tunas Bakti Nusantara, Poso), aku melihat bagaimana para orang tua berjuang memahami peran mereka di tengah tekanan hidup.
Di balik tantangan ekonomi dan sosial, selalu ada kerinduan untuk menjadi lebih baik bagi keluarga.
Seperti kata Werner dan Smith (1992), “Resilience is dynamic and relational” ia tumbuh ketika kita saling terhubung.
Dari Luka Menuju Kedewasaan
Aku juga belajar bahwa resilience bukan berarti tidak terluka.
Ia justru lahir dari luka yang diolah dengan sadar. Viktor Frankl (1959) menulis bahwa penderitaan menjadi bermakna ketika kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup.
Aku sendiri pernah merasakannya melalui kehilangan, kegagalan, rasa tidak berdaya; dan dari sanalah aku belajar untuk tidak melarikan diri dari rasa sakit, tetapi duduk bersamanya, mendengarnya, dan membiarkannya berbicara.
Dari situ lahir bukan hanya pemulihan, tapi kedewasaan batin.
Menyalakan Kembali Benih Ketahanan
Saat aku berbicara tentang resilience di ruang pelatihan, aku tidak berbicara sebagai seseorang yang sudah selesai, tapi sebagai seseorang yang terus belajar.
Aku percaya setiap orang membawa benih ketahanan dalam dirinya. Kadang tertutup oleh rasa takut, kadang oleh rasa bersalah, tapi ia tidak pernah hilang.
Tugas kita adalah membantu menyalakan kembali benih itu dengan empati, kesadaran, dan cinta.
Karena pada akhirnya, resilience adalah tentang keseimbangan antara ilmu dan hati, antara logika dan makna.
Manusia tidak diciptakan untuk sempurna, tetapi untuk tumbuh.
Dan dalam setiap perjumpaan baik di ruang terapi yang hening maupun di tengah riuhnya pelatihan dengan ratusan peserta, aku selalu melihat keajaiban yang sama: ketika seseorang memilih untuk tetap membuka hati meski pernah terluka, di situlah resilience hidup dan memulihkan.
Sebuah refleksi dari : Leonardus Devi